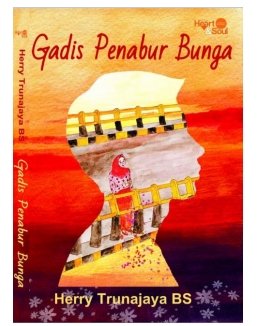“Kau masih beruntung dari aku, Ta,” kata Bagas, sepulang sekolah, suatu sore.
“Kok?” Aku menatap wajah Bagas yang bermata bagus.
“Karena ayahmu, Om Effendi selamat dari terjangan peluru di Bobonaro dan bisa berkumpul kembali dengan keluargamu, seperti melihatmu lahir dan membesarkanmu, sementara aku cuma tau wajah ayahku dari potret usangnya dan cerita keheroikannya,” kata Bagaskara, sendu.
Aku menghentikan langkah. Bagas juga. Mata kami beradu di udara. Aku melihat pijar duka di mata bagusnya.
“Tapi kami semua sayang dan bangga terhadap dirimu,” suaraku bagai tercekat.
Bagaskara tampak tersenyum. Lalu ia meraih tangan kananku dan kembali melangkah. Aku menyeka sudut mataku. Halte bus masih beberapa puluh meter lagi.
Sebagai ibu, Bibi Ratih tentu saja merasa amat bahagia dan bangga ketika Bagaskara berhasil lulus ujian akhir nasional dengan predikat sebagai murid teladan. Bagaskara memang anak yatim dan ibu yang membesarkannya hanya seorang pekerja di pabrik pengepakan udang, namun Bagaskara tak pernah merasa minder. Bagaskara selalu tampil sebagai juara di sekolah setiap tahunnya.
Aku yang sudah berteman dan bersahabat dengan Bagaskara sejak masih sama-sama bersekolah di TK Islam Istiqomah, tentu saja juga ikut merasa bangga dengan prestasi belajar yang diraihnya. Aku sendiri hanya bisa menempatkan diri di jajaran lima besar rangking sekolah. Masih kalah jauh dari Bagaskara, Lilka, Dul dan Ahmad yang masing-masing menduduki peringkat pertama hingga keempat.
Bibi Ratih tidak saja bangga karena telah mengantarkan Bagaskara menjadi seorang yang terpandai di sekolah, namun juga bangga karena Bagaskara tumbuh besar menjadi seorang pemuda yang tekun dan taat beribadah. Suara Bagaskara yang cukup merdu jika sedang melantunkan ayat-ayat suci Al Qur’an di Surau banyak dikagumi anak-anak gadis, teman-teman aku dan Bagaskara. Dan diam-diam aku merasa cemburu jika kulihat Bagaskara ngobrol dengan teman-teman gadis sebayaku.
Hanya beberapa bulan menganggur, akhirnya Bagaskara mendapatkan pekerjaan di kota. Sedangkan aku bekerja di sebuah toko alat-alat pertanian di desa kami. Tapi yang membuat hatiku bertanya-tanya, Bagaskara tidak bersedia memberitahukan nama perusahaan tempatnya bekerja.
“Pokoknya ada deh,” katanya dengan senyum tipis. Bagai menyimpan misteri. Membuat aku makin penasaran.
“Apa sih nama perusahaannya, apa perusahaan migas, tambang batu bara atau tambang intan,” desakku.
“Pokoknya bukan toko alat-alat pertani…”
“Sok kamu!” rajukku. Bagas malah tertawa, memperlihatkan deretan giginya yang putih rapi dan membuat kedua mata hitamnya bagai terbenam. Itulah kenangan indah yang kini bermain-main di benakku.
***
SEMALAMAN aku dan Bibi Ratih tidak bisa memicingkan mata sekejap pun. Gambar-gambar korban pemboman di layar kaca televisi itu terus membayang di kelopak mata kami. Mata Bibi Ratih tampak sembab karena menangis. Aku memang menemani Bibi Ratih menginap di rumahnya. Aku ingin berbagi kecemasan akan ketidakpastian Bagaskara yang sama-sama kami sayangi dan cintai sebagai seorang ibu terhadap anaknya dan sebagai seorang gadis terhadap kekasihnya.
Hujan yang turun mengguyur bumi dengan cukup deras makin menambah galau perasaan dan hati kami. Bagaimana tidak, Bagaskara tidak juga berhasil aku hubungi melalui kontak telepon. Dan aku semakin dilanda ketidaktahuan harus berbuat apa, karena Bagaskara juga tidak ada mengontakku. Juga Bibi Ratih. Apakah Bagaskara menjadi salah seorang korban? Tapi, dari berita semalam, penyiar wanita yang dengan suara sedih tidak ada menyebutkan nama Bagaskara atau Bagas saja.
Ketika matahari mulai menyinari bumi yang basah sehabis dibasuh hujan semalam, aku bergegas membaca berita di koran pagi dengan perasaan berdebar tak karuan. Aku sedikit merasa lega karena dari deretan nama-nama korban tidak ada nama kekasihku: Bagaskara! Ke mana kau Bagas, kenapa aku tidak bisa mendengar suaramu, agar aku bisa memastikan kau sehat-sehat saja…, gumam hatiku galau makin tak karuan.
Bagaskara seperti hilang ditelan bumi. Berita di layar televisi dan koran terus aku simak. Terpaksa aku tidak turun bekerja dan risikonya gajiku dipotong oleh pemilik toko tempatku bekerja. Tapi aku tidak peduli. Aku lebih peduli dengan Bagas yang sampai detik ini tidak aku ketahui keberadaannya. Aku tetap saja gelisah, meski berita di televisi dan koran-koran tidak menyebutkan nama Bagaskara, karena masih ada korban-korban yang belum bisa dikenali. Siapa tahu korban yang belum dikenali itu salah satunya Bagaskara, oh!
Aku kembali merasakan langit seperti runtuh dan menghimpit tubuhku, siang yang mendung itu.
Berita di layar televisi yang masih menyajikan peristiwa biadab itu sebagai berita utama menyebut nama Bagaskara akhirnya.
Aliran darah dan jantungku bagai berhenti mengalir dan berdetak. Nama Bagaskara disebut penyiar wanita berwajah cantik itu bukan sebagai korban, tapi sebagai komplotan yang diduga kuat sebagai pelaku pemboman yang dikutuk!
Wajah tampan Bagaskara jelas disorot kamera wartawan bersama beberapa orang rekannya. Aku ternganga bagai tidak percaya, tapi kemudian tubuhku limbung dan ambruk di lantai bagai selembar daun yang lepas dari tangkainya. Aku masih menyadari kalau Bibi Ratih yang duduk di sisiku menangkap tubuhku. Namun kemudian semuanya menjadi gelap.
Ketika sadar, aku dapati Bibi Ratih duduk di sisiku yang terbaring di kasur. Aku mengitarkan pandangan mataku yang belum sepenuhnya sempurna. Ada ayah, ibu, adikku Galuh dan beberapa wajah tetangga. Wajah mereka semua tampak suram. Mereka semua tentu tidak percaya dengan kenyataan, kalau ternyata Bagaskara menjadi salah seorang dari komplotan yang melakukan pemboman yang dikutuk itu. Apalagi umur Bagaskara baru menginjak tahun ke dua puluh dua.
Aku melihat wajah Bibi Ratih yang tampak tenang. Tapi aku tahu hatinya amat terluka. Hati ibu mana yang tidak kecewa dan sedih dengan apa yang telah diperbuat anak tersayangnya, harapan dan kebanggaan seorang ibu. Ya, Bagas telah mengecewakan ibu yang telah bersusah payah membesarkan dan menyekolahkan. Aku saja, kekasihnya, amat kecewa dan terpukul menghadapi kenyataan ini!
Terbayang di pelupuk mataku yang hangat akan hukuman yang berat menghadang Bagas. Hukuman mati sudah pasti menanti Bagas dan komplotannya. Aku merasa ganjaran itu cukup setimpal. Namun diriku merasa tak kuat membayangkan kemungkinan itu semua. Aku lalu bangun dan memeluk Bibi Ratih. Aku menumpahkan tangisku tanpa peduli dengan orang-orang di sekitarku. Hatiku begitu pepat.*(Bersambung ke Bagian 3|Herry Trunajaya BS)