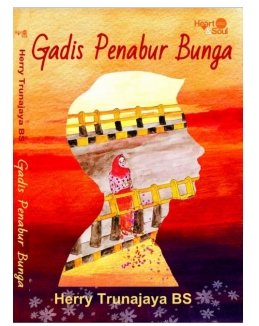LANGIT seperti runtuh dan menghimpit tubuhku. Betul-betul aku tidak percaya dengan apa yang tersaji di hadapanku, meski hanya di dalam layar kaca televsisi. Tetapi pemandangan itu sungguh-sungguh telah meremukkan perasaanku sebagai seorang manusia. Sungguh biadab dan terkutuk para pelaku pemboman yang telah menewaskan orang-orang yang tidak bersalah dan berdosa.
Tubuh-tubuh yang berlumur darah dan bahkan ada yang tidak bisa dikenali lagi. Mereka tewas sebagai korban dari orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Aku hanya bisa mengurut dada dan bergidik, apalagi Bagaskara berada di daerah yang terbencana oleh kebiadaban manusia itu.
“Oh, gusti Allah semoga Bagaskara tidak menjadi salah satu korban…,” rintihku dengan tetap menyimak suara pembawa berita dan gambar di layar televisi yang sudah lebih dari tiga puluh menit terus menyajikan bencana di negeri tercinta ini.
Sungguh aku tidak bisa mengerti mengapa dalam tahun-tahun terakhir ini negeriku yang tercinta terus diamuk bencana, baik itu karena murka alam atau karena kebiadaban sesama manusia. Saling sikut dan bahkan saling bantai demi suatu ambisi. Malah lebih kejam dari binatang liar dan buas.
Rasa khawatir mulai merambati tubuhku, karena Bagaskara tidak menyambut kontak telepon, baik melalui kediamannya maupun ponselnya. Ini tidak pernah terjadi. Biasanya, setiap kali aku mengontaknya, tak cukup lima detik Bagaskara sudah menyahut dengan salam khasnya: “Assalamu’alaikum Sayangku….” Tetapi hari ini, dimana pemboman itu terjadi, aku tidak bisa mendengarkan sahutannya untuk memastikan kalau dirinya baik-baik saja dan sehat wal-afi’at. Oh, dimanakah dirimu, Sayangku…
Aku pun menelpon Bibi Ratih, dan ternyata ibu Bagaskara juga kehilangan kontak dengan anak tersayangnya sejak peristiwa pemboman itu ramai disiarkan stasiun televisi di tanah air.
“Iya Nak Julita, Bibi juga sampai saat ini ndak bisa mengontak Bagas. Bibi cemas kalo ada apa-apa terjadi dengan Bagas,” suara Bibi Ratih terdengar begitu khawatir.
“Tenang ya Bi. Moga-moga aja ndak ada apa-apa yang terjadi sama Mas Bagas. Kita berdoa aja sama Allah, agar Mas Bagas diberi perlindungan-Nya,” kataku, mencoba menghibur kecemasan dan kekhawatiran hati Bibi Ratih. Kecemasan dan kekhawatiran yang juga melanda hatiku sendiri. Hati seorang gadis yang amat mencintai dan menyayangi kekasih hatinya.
Sebagai sesama perempuan, meski aku baru saja lulus SMA, tetapi aku juga dapat merasakan bagaimana panik dan cemasnya Bibi Ratih dengan nasib Bagaskara. Aku paham betul bagaimana sayang dan cintanya Bibi Ratih terhadap Bagaskara yang telah ditinggal pergi oleh ayahnya untuk selama-lamanya.
“Bibi sangat menyayangi Bagas. Ia menjadi pengganti ayahnya yang meninggal di medan pertempuran,” ungkap Bibi Ratih ketika sore itu aku berkunjung ke rumahnya untuk belajar bersama Bagaskara.
Aku melihat pijar bangga di mata dan diraut wajah Bibi Ratih yang masih terlihat cukup cantik. Tapi Bibi Ratih tidak pernah lagi mau menikah, karena ia tidak pernah akan menggantikan kedudukan suaminya, Om Riswan, ayahBagaskara yang telah gugur di daerah Bobonaro, Timor-Timur.
“Sebagai istri seorang prajurit, bibi ikhlas dengan kepergian suami bibi, meski akhirnya daerah itu kembali memisahkan diri dari negeri kita tercinta ini,” tutur Bibi Ratih padaku.
Ayahku yang juga tentara dan keluarga Bibi Ratih memang bertetangga. Rumah kami hanya berjarak satu blok. Ayah juga pernah bercerita kalau Om Riswan telah gugur sebagai bunga bangsa di medan pertempuran. Malah ayah selalu menggebu-gebu dan tampak begitu bangga kalau mengenang kisah pertempurannya itu, dan merasa sedih karena harus kehilangan sahabatnya, Om Riswan.
Bagaskara memang tidak pernah tahu wajah asli ayahnya. Ia hanya tahu wajah ayahnya melalui potret ketika ibu dan ayahnya akan menikah, ketika itu Bagaskara masih berada dalam kandungan ibunya. Bibi Ratih memang tengah hamil muda ketika Om Riswan dan ayahku mendapatkan tugas dari negara menuju ke medan pertempuran. Meski dengan berat hati, Bibi Ratih tetap harus rela melepaskan suaminya. Begitu juga dengan ibuku yang katanya, waktu itu baru mulai ngidam. Jadi, usia Bagas dan aku hanya terpaut beberapa bulan saja.
Om Riswan gugur di malam ketika Bagaskara lahir. Maka, tinggallah Bibi Ratih hidup berdua dengan Bagaskara. Makin beranjak dewasa postur dan wajah Bagaskara makin mirip dengan ayahnya, sehingga Bibi Ratih makin sayang terhadapnya. Bukan itu saja, Bagaskara juga kalau melakukan sesuatu seperti menulis selalu dengan tangan kiri atau kidal, sama seperti kebiasaan ayahnya.
“Bagas itu memang amat mirip dengan almarhum ayahnya. Tidak saja dari postur dan wajahnya, tapi juga perilakunya, seperti lebih sering menggunakan tangan kirinya kalo sedang melakukan sesuatu, menulis misalnya,” tutur Bibi Ratih yang juga selalu memperlakukan aku dengan penuh kasih sayang. Aku memang pernah mendengar bisik-bisik ibuku dan Bibi Ratih, bahwa mereka setuju menjodohkan aku dan Bagaskara jika kami dewasa nanti. Aku dan Bagaskara tentu saja bahagia, karena kami memang sudah saling mencintai. Saat ini aku dan Bagaskara memang masih menempuh pendidikan akhir di SMA yang sama.*(Bersambung ke Bagian 2|Herry Trunajaya BS)